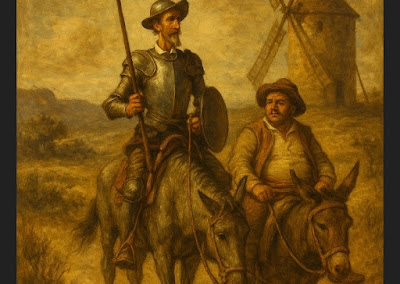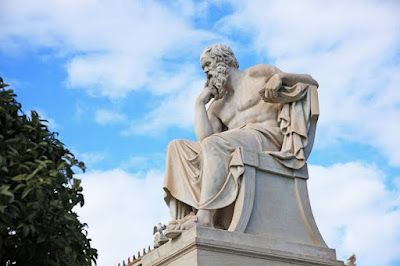|
| Tragedy dan Komedy Teater Yunani - SutianaMenulis (Wikipedia) |
Namun, berbeda dengan tragedi yang lebih serius dan dramatis, komedi pada awalnya penuh dengan ejekan, kata-kata kasar, serta unsur keburukan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mendorong kesuburan.
Dalam festival Dionysus, para peserta seringkali mempersembahkan pertunjukan yang penuh kelucuan dan kegilaan, yang mungkin menjadi asal mula komedi sebagai bentuk teater.
Salah satu elemen penting dalam komedi awal adalah parabasis, yaitu bagian dalam pertunjukan di mana paduan suara menghentikan aksi utama dan memberikan komentar mengenai peristiwa-peristiwa terkini serta tokoh-tokoh yang ada pada masa itu.
Parabasis ini kemungkinan besar berasal dari pesta-pesta dan perayaan-perayaan yang berfokus pada pengusiran kejahatan dan perayaan kesuburan, yang merupakan bagian integral dari ritual Dionysus.
Komedi Yunani juga memiliki akar dalam komedi sekuler yang berkembang di Megara, sebuah kota di Yunani, yang kemudian dibawa dan dikembangkan lebih lanjut oleh Epicharmus di Syracuse sekitar abad ke-6 hingga abad ke-5 SM.
Komedi sekuler ini tidak melibatkan paduan suara, dan lebih fokus pada cerita-cerita ringan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Epicharmus, seorang dramawan dari Syracuse, memodifikasi bentuk komedi ini sehingga menjadi lebih terstruktur dan terorganisir dalam bentuk pertunjukan teater yang formal.
Selain itu, terdapat juga bentuk komedi yang lebih realistis, yaitu mime, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dalam sketsa-singkat dan sederhana.
Mime ini tidak hanya memperlihatkan karakter-karakter yang lucu, tetapi juga menggambarkan interaksi sosial yang penuh dengan humor dan ketegangan.
Meskipun sebagian besar karya mime ini hanya tersisa dalam bentuk fragmen-fragmen, karya-karya tersebut memiliki pengaruh besar pada bentuk dialog dalam karya-karya Plato serta pada mime yang berkembang di periode Hellenistik.
Di Athena, komedi akhirnya menjadi bagian resmi dari perayaan Dionysus pada tahun 486 SM, yang menandai titik balik dalam sejarah teater komedi Yunani.
Komedi mulai diterima sebagai bagian penting dari festival budaya dan menjadi lebih terstruktur sebagai bentuk teater yang memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat.
Pada masa ini, komedi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan kritik sosial terhadap pemerintah, kelas elit, serta berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat.
Dengan perkembangan ini, komedi Yunani semakin matang dan mulai menunjukkan keragaman dalam gaya dan tema.
Komedi tidak lagi hanya berfokus pada lelucon dan humor kasar, tetapi juga mulai mengangkat tema-tema sosial, politik, dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih halus dan terkadang satirikal.
Karya-karya komedi dari tokoh-tokoh seperti Aristophanes menjadi salah satu contoh terbaik dari bagaimana komedi Yunani mampu bertahan dan beradaptasi dengan zaman, serta tetap relevan dengan masalah-masalah sosial yang ada.
Melalui perjalanan panjangnya, komedi Yunani berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pilar utama dalam sejarah teater, memberikan pengaruh besar terhadap bentuk-bentuk teater komedi di masa depan, baik di dunia Barat maupun di belahan dunia lainnya.***
Source: Britannica

.jpeg)